Oleh: Eko Mardiono
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah direvisi oleh DPR sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. MK memutuskan batas minimum perkawinan dalam UU Perkawinan Pasal 7 ayat (1) supaya direvisi dan memberi tenggat waktu tiga tahun kepada DPR untuk melakukan perubahan.
Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan menetapkan, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. DPR pun merevisi dan mengesahkan batas minimum usia perkawinan 19 tahun bagi pria dan wanita.
Efektifkah upaya pendewasaan usia perkawinan dengan hanya menaikkan usia minimum perkawinan bagi wanita dari 16 tahun menjadi 19 tahun tanpa menghapus Pasal 7 ayat (2) yang memberikan dispensasi perkawinan di bawah umur dengan izin Pengadilan?
Efektifkah upaya pendewasaan usia perkawinan dengan hanya menaikkan usia minimum perkawinan bagi wanita dari 16 tahun menjadi 19 tahun tanpa menghapus Pasal 7 ayat (2) yang memberikan dispensasi perkawinan di bawah umur dengan izin Pengadilan?
Sangat menarik tulisan Ghufron Su’udi yang berjudul, “Sudah Cukupkah Revisi UU Perkawinan?” Ghufron menegaskan, walaupun sudah ada revisi UU Perkawinan namun perkawinan anak akan tetap berlangsung dan upaya pendewasaan usia perkawinan hanya menjadi angan-angan semata.
Hal itu karena Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan yang memberikan peluang adanya pengecualian perkawinan di bawah umur tidak sekalian direvisi. Dengan hanya merevisi Pasal 7 ayat (1), maka permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur akan semakin meningkat, demikian Ghufron (KR, 24/09/2019).
Betulkah demikian? Haruskah Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan yang memberikan peluang perkawinan di bawah umur dengan dispensasi Pengadilan harus dihapus?
Secara teoretis, Undang-undang yang mengatur usia minimum perkawinan ada tiga kategori, yaitu: (1) Undang-undang yang lebih menjamin hak-hak, yakni yang menetapkan usia 18 tahun sebagai usia minimum perkawinan, baik untuk laki-laki maupun perempuan;
(2) Undang-undang yang dapat digunakan untuk melindungi hak-hak, yakni yang memperbolehkan pengecualian terhadap usia minimum 18 tahun tanpa batasan, tetapi mengharuskan izin orangtua untuk perkawinan di bawah usia 21 tahun;
(3) Undang-undang yang diskriminatif, yaitu yang menetapkan usia di bawah 15 tahun sebagai usia minimum perkawinan, atau menetapkan pubertas sebagai ukuran kapasitas untuk menikah, atau tidak menentukan usia minimum perkawinan (WLUML London, Mengenali. 2007, hlm. 67).
(2) Undang-undang yang dapat digunakan untuk melindungi hak-hak, yakni yang memperbolehkan pengecualian terhadap usia minimum 18 tahun tanpa batasan, tetapi mengharuskan izin orangtua untuk perkawinan di bawah usia 21 tahun;
(3) Undang-undang yang diskriminatif, yaitu yang menetapkan usia di bawah 15 tahun sebagai usia minimum perkawinan, atau menetapkan pubertas sebagai ukuran kapasitas untuk menikah, atau tidak menentukan usia minimum perkawinan (WLUML London, Mengenali. 2007, hlm. 67).
Berdasarkan Tiga kategori di atas, maka revisi UU Perkawinan ini masuk kategori kedua. Yaitu, Undang-undang yang dapat digunakan untuk melindungi hak-hak, yakni yang memperbolehkan pengecualian terhadap usia minimum 18 tahun tanpa batasan, tetapi mengharuskan izin orangtua untuk perkawinan di bawah usia 21 tahun.
Usia minimum revisi UU Perkawinan ini pun 19 tahun bagi pria dan wanita, serta harus mendapat izin kedua orang tua bagi yang belum mencapai umur 21 tahun (Pasal 6 ayat 2 UU Perkawinan).
Usia minimum revisi UU Perkawinan ini pun 19 tahun bagi pria dan wanita, serta harus mendapat izin kedua orang tua bagi yang belum mencapai umur 21 tahun (Pasal 6 ayat 2 UU Perkawinan).
Mungkinkah revisi UU Perkawinan ditetapkan tanpa pengecualian atas batas minimum perkawinannya 19 tahun bagi pria dan wanita?, sehingga masuk kategori pertama, yaitu Undang-undang yang lebih menjamin hak-hak?
Perihal ini harus dilihat dari berbagai aspeknya. Selama penulis bertugas di KUA Kecamatan selama 23 tahun, hampir semua perkawinan di bawah umur terjadi karena hamil pranikah akibat pergaulan bebas.
Oleh karena itu, apabila pengecualian perkawinan di bawah umur dengan dispensasi Pengadilan dihapus, lantas bagaimana status dan nasib anak yang masih dalam kandungan? Akankah ia akan lahir sebagai anak seorang ibu tanpa bapak? Bagaimana dampak psikis dan sosial ekonomi bagi anak yang bersangkutan?
Oleh karena itu, apabila pengecualian perkawinan di bawah umur dengan dispensasi Pengadilan dihapus, lantas bagaimana status dan nasib anak yang masih dalam kandungan? Akankah ia akan lahir sebagai anak seorang ibu tanpa bapak? Bagaimana dampak psikis dan sosial ekonomi bagi anak yang bersangkutan?
Menurut pengalaman penulis sebagai Penghulu Madya, anak seorang ibu menjadi terisak menangis tatkala berikrar dan bermohon supaya dinikahkan dengan wali hakim sebab tidak mempunyai wali nasab ayah kandung.
Memang Kitab Undang-undang Hukum Perdata membuka peluang Pengesahan Anak (Pasal 272) dan Pengakuan Anak (Pasal 280) serta mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya (Putusan MK No. 46-PUU-VIII-2010).
Walaupun demikian, dalam Akte Kelahirannya ia tetap sebagai anak seorang ibu yang akan berdampak terhadap perkembangan psikis dan sosial ekonomi anak yang bersangkutan.
Walaupun demikian, dalam Akte Kelahirannya ia tetap sebagai anak seorang ibu yang akan berdampak terhadap perkembangan psikis dan sosial ekonomi anak yang bersangkutan.
Dengan demikian, menurut hemat penulis revisi UU Perkawinan untuk saat ini tidak harus menghapus pasal pengecualian perkawinan di bawah umur dengan dispensasi Pengadilan.
Untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur, maka perlu digencarkan kegiatan pendewasaan usia perkawinan dan peningkatan mental spiritual keagamaan remaja, sehingga terhindar dari hamil pranikah.
Untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur, maka perlu digencarkan kegiatan pendewasaan usia perkawinan dan peningkatan mental spiritual keagamaan remaja, sehingga terhindar dari hamil pranikah.
Dengan demikian, kalaupun ada hakim Pengadilan menjadi leluasa dalam memutuskan permohonan perkawinan di bawah umur karena tiadanya janin dalam kandungan yang juga harus dilindungi hak-haknya.
 RSS Feed
RSS Feed Twitter
Twitter




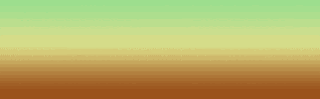


0 comments:
Posting Komentar